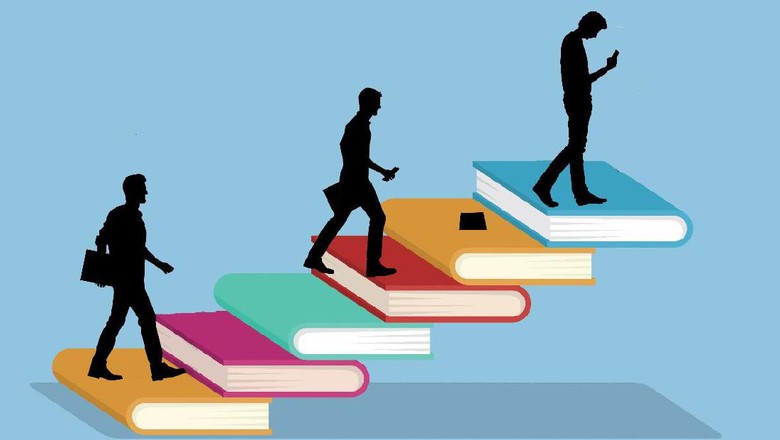 Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Dalam setahun terakhir beberapa sarjana telah mengkritik kebijakan publikasi ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) yang menjadikan Scopus sebagai ukuran reputasi intelektual. Rizqy Amelia Zein (2018) misalnya menyatakan kebijakan tersebut justru mendorong banyak akademisi untuk melakukan kecurangan. Antara lain terlalu over mensitasi (mengutip, merujuk) karya sendiri dalam menulis karya-karya berikutnya yang belum tentu relevan, atau bahkan membentuk kartel sitasi (kutipan, rujukan) untuk saling mensitasi satu sama lain. Dikatakan curang karena kartel sitasi tersebut asal mensitasi walaupun topiknya tidak relevan antara karya yang disitasi dengan karya yang mensitasi.
Mensitasi sesungguhnya adalah upaya untuk membangun satu fondasi epistemologis yang kuat mengenai suatu argumen berdasarkan pada argumentasi ilmiah yang telah dikemukakan oleh para cendekiawan sebelumnya. Oleh karena itu, mensitasi karya terdahulu membutuhkan kejelian dan ketelatenan untuk menemukan karya yang topiknya berdekatan atau bahkan sama dengan karya yang sedang ditulis. Makin banyak sitasi relevan yang ditulis juga menunjukkan kepakaran sang penulis disebabkan oleh kekayaan dan penguasaan informasi mengenai tema tertentu yang ditulisnya. Kartel sitasi paradoks dengan hakikat dan nilai-nilai kecendekiawanan tersebut.
Cara berikutnya adalah langsung saja menulis manuskrip untuk dikirim dan terbitkan di prosiding (kumpulan paper akademis) konferensi internasional yang akan dipublikasikan dan diindeks oleh Scopus dan beberapa pengindeks internasional lain. Cara ini memang lebih praktis, tapi harus rela bayar lumayan. Praktis karena menulis di prosiding tidak ditelaah dan seleksi secara ketat, termasuk oleh Scopus (Surya Dalimunthe, 2018). Seleksi hanya dilakukan di level panitia penyelenggara konferensi dan penerbit internasional yang akan mempublikasikan prosiding. Sementara itu pihak Scopus tidak menyeleksi ketat substansi prosiding.
Ketika rata-rata institusi penyelenggara konferensi internasional butuh peserta banyak untuk menunjang operasional acara atau bahkan menangguk untung, tim penyeleksi (reviewers) tentu tidak akan mengetatkan proses seleksi manuskrip. Hal itu disebabkan oleh prinsip, makin banyak peserta konferensi yang ikut, makin banyak pula uang masuk ke panitia untuk membayar penyelenggaraan acara, honor tim penyeleksi, dan membayar ke penerbit internasional yang bersedia mempublikasikan prosiding hasil konferensi untuk diindeks oleh Scopus. Perlu diingat juga bahwa Scopus adalah bagian dari raksasa bisnis penerbit internasional, Elsevier. Artinya, ada perputaran uang di situ.
Sekarang bahkan muncul Event Organizer (EO) konferensi dan seminar. Mereka menawarkan pengelolaan acara konferensi kepada pihak perguruan tinggi sampai menjanjikan publikasi prosidingnya akan diindeks oleh Scopus. Apapun itu para dosen sekarang rata-rata kalau mendengar prosiding akan diindeks oleh Scopus akan tertarik ikut. Hal itu karena menerbitkan manuskrip di jurnal bereputasi internasional dan terindeks Scopus memang tidak mudah. Jurnal ilmiah yang sudah bereputasi memiliki kebijakan seleksi yang ketat. Soal kualitas substansi manuskrip pasti jadi perhatian utama, termasuk kebaruan, temuan, dan kontribusi keilmuannya.
Semua hal tersebut bermula dari kebijakan Kemenristek Dikti agar para dosen di lingkungan perguruan tinggi berpacu untuk berkontribusi meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di kancah internasional. Motivasi untuk menyaingi Malaysia dan negara-negara tetangga terlihat betul. Sayang kemudian pemahaman jurnal bereputasi internasional tersebut disimplifikasi menjadi jurnal yang diindeks oleh Scopus. Bahkan karena sulit menembus jurnal yang diindeks Scopus, maka prosiding yang diindeks Scopus pun tidak apa-apa, yang penting Scopus. Hal inilah yang harus dikaji dan dipahami ulang.
Pilihan Publikasi
Sebenarnya jurnal ilmiah adalah sarana komunikasi hasil telaah dan temuan-temuan ilmiah bidang-bidang keilmuan tertentu. Kebetulan Scopus adalah lembaga pengindeks yang cukup selektif dalam mengindeks jurnal-jurnal ilmiah di kancah internasional. Tidak masalah sebenarnya memacu dosen untuk mempublikasikan manuskrip ilmiahnya di jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks Scopus. Namun sejauh dapat kita amati, Scopus ternyata memiliki kelamahan, yaitu pada indeksasi prosiding konferensi atau seminar internasional. Faktanya, banyak prosiding lolos begitu saja, namun dengan isi artikel-artikel ilmiah akademik yang tidak terjaga kualitasnya.
Sebenarnya jurnal ilmiah adalah sarana komunikasi hasil telaah dan temuan-temuan ilmiah bidang-bidang keilmuan tertentu. Kebetulan Scopus adalah lembaga pengindeks yang cukup selektif dalam mengindeks jurnal-jurnal ilmiah di kancah internasional. Tidak masalah sebenarnya memacu dosen untuk mempublikasikan manuskrip ilmiahnya di jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks Scopus. Namun sejauh dapat kita amati, Scopus ternyata memiliki kelamahan, yaitu pada indeksasi prosiding konferensi atau seminar internasional. Faktanya, banyak prosiding lolos begitu saja, namun dengan isi artikel-artikel ilmiah akademik yang tidak terjaga kualitasnya.
Sebenarnya pilihan untuk mengkomunikasikan telaah dan temuan ilmiah bukan hanya di jurnal ilmiah dan prosiding konferensi saja. Keduanya memang lebih eksklusif karena dibuat untuk tujuan ilmiah, yakni pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak sembarang orang dapat memahami bahasa akademik yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Konferensi, seminar, ataupun simposium juga diselenggarakan sebagai ajang bertemu para akademisi untuk berbagi hasil telaah dan temuan ilmiah. Pada kesempatan tersebut presentasi dilakukan, makalah dikritik dan diberi masukan, serta kerja sama pengembangan keilmuan coba dijajagi.
Oleh karena itu, manuskrip yang dipresentasikan di konferensi sejatinya bukan merupakan bentuk final publikasi. Forum-forum ilmiah tersebut justru merupakan ajang memperoleh kritik dan masukan untuk memperbaiki manuskrip. Penyelenggaraan perhelatan konferensi, seminar, dan simposium di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia memang terbagi dua, antara yang serius atau sekadar untuk mendorong publikasi terindeks oleh pengindeks internasional, terutama Scopus. Jenis kedua inilah yang agaknya cenderung menggadaikan reputasi intelektual hanya demi terindeks Scopus melalui prosiding.
Akademisi perguruan tinggi yang ingin mengamankan tunjangan bulanannya (terutama level Lektor dan Profesor) memang cenderung terobsesi publikasi di Scopus. Banyak grup WhatsApp, Instragram, dan lainnya beramai-ramai berbagi agenda acara konferensi dengan iming-iming manuskripnya akan dipublikasikan dalam prosiding yang terindeks Scopus. Tak banyak yang mencoba belajar menjalani proses ketat dalam komunitas intelektual untuk betul-betul menguji telaah dan temuan riset dengan mengirimkan manuskripnya ke jurnal-jurnal bereputasi. Sekarang akan mudah kita jumpai banyak prosiding terindeks Scopus atau pengindeks internasional lain berisi artikel-artikel dari penulis Indonesia dengan kualitas yang seadanya.
Sebenarnya selain jurnal ilmiah dan prosiding, publikasi buku juga dapat menjadi media komunikasi ilmiah yang bagus. Atmosfer akademik di Indonesia secara historis lebih mengenal buku ketimbang jurnal ilmiah. Tahun 1960-an hingga akhir 1990-an banyak cendekiawan yang pakar dalam bidang-bidang tertentu dikenal melalui publikasi bukunya ketimbang artikel ilmiah yang terbit di jurnal-jurnal ilmiah. Dalam dunia pendidikan, nama-nama besar seperti Prof. Conny Semiawan, Prof. H.A.R. Tilaar, Raka Joni, dikenal melalui buku-bukunya yang menjadi bacaan wajib mahasiswa program studi kependidikan.
Namun penerbit-penerbit buku di Indonesia memang belum mengutamakan keterjagaan mutu terbitannya. Dengan demikian, reputasi penulis yang mempublikasikan karyanya relatif terjaga hanya melalui dua pihak; pertama diri penulis sendiri yang harus betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, dan kedua pihak pemberi kata pengantar dari pakar yang ikut membaca gagasan buku tersebut. Tidak banyak penerbit yang memiliki tim pakar untuk sekadar menjadi pembaca profesional di bidang tertentu. Berbeda dengan tradisi penerbit-penerbit besar di dunia internasional seperti Springer, SAGE, Continuum, Routledge, dan sejenisnya.
Routledge misalnya, memiliki semacam editorial board yang dipimpin oleh William F. Pinar, pakar kurikulum rekonseptualis internasional, untuk mengkaji, menyeleksi, dan memprogram penerbitan buku-buku akademik bertema kurikulum. Oleh karena itu, buku-buku tentang kurikulum yang diterbitkan oleh Routledge terjaga betul kualitasnya. Hal itu karena Pinar yang terlibat dalam komunitas ahli kurikulum paham betul kualifikasi para calon penulis, selain itu juga Pinar dan anggota tim yang difasilitasi oleh Routledge paham betul substansi naskah buku. Hal ini penting mengingat buku akademik harus jelas betul soal teori-teori yang disajikan, juga kebaruan telaah dan temuan dalam bidang tersebut.
Sementara itu penerbit-penerbit Indonesia yang menerbitkan buku-buku akademik masih lebih banyak mempertimbangkan potensi pasar. Naskah yang diwajibkan dibaca oleh mahasiswa dalam mata kuliah tertentu akan lebih diutamakan. Di sini celahnya muncul, karena tim penerbit tidak memiliki tim seleksi yang berasal dari komunitas bidang keilmuan tertentu-yang biasanya berasal dari asosiasi bidang keilmuan, profesi, atau pakar, maka penerbit akan kesulitan menilai substansi materi yang ditulis oleh penulis buku. Soal kebenaran pengertian teoretik tertentu, atau juga kebaruan dalam bidang keilmuan tertentu, pasti para cendekiawan yang terlibat dalam komunitas ilmiah lebih tahu ketimbang para pengelola penerbitan.
Masalah lain muncul ketika menerbitkan buku sebenarnya sangat mudah. Terlebih ketika sesama penerbit, terutama di level bawah, saling berebut pasar mencari calon penulis. Memperoleh ISBN atau bahkan Hak Cipta buku sangat mudah. Asal ada naskah, penerbit akan mengurusnya sampai dapat ISBN. Terlebih jika calon penulis ikut urun biaya cetak, tentu penerbit senang sekali. Tiadanya seleksi dari penerbit memudahkan orang menerbitkan buku hingga memperoleh ISBN. Pihak yang mengeluarkan ISBN pasti tidak mengontrol hingga substansi naskah. Begitu pula pihak yang mengeluarkan Hak Cipta.
Oleh karena itu, jangan heran banyak akademisi produktif menerbitkan buku dengan ISBN dan bahkan memperoleh Hak Cipta. Produktif menulis buku ber-ISBN, bahkan memiliki Hak Cipa, tidak selalu menunjukkan kualitas karya yang tinggi. Jika ingin tahu kualitasnya, telaah secara mendalam naskah buku tersebut di lingkungan komunitas intelektual yang sesungguhnya. Prinsip ini sama berlaku untuk para akademisi yang memiliki H-Index tinggi di Sinta maupun Scopus, telaah dulu artikelnya secara akademik, karena sekarang banyak akademisi yang memiliki H-Index tinggi, namun berasal dari praktik kartel sitasi atau publikasi prosiding-prosiding yang diindeks oleh Scopus yang tidak ditelaah secara ketat sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ilmiah.
Selain itu menulis artikel populer di media massa juga potensial sebagai media komunikasi telaah dan temuan ilmiah. Berbeda dengan jurnal ilmiah, konferensi ilmiah, atau buku, artikel populer lebih diarahkan untuk komunitas pembaca umum. Hanya saja media umum memang bukan media ilmiah akademik, hingga seleksi soal sisi akademiknya relatif longgar. Namun, setidaknya justru media massa seperti ini susah diterabas oleh orang-orang yang ingin lekas terpublikasikan artikelnya. Sayang, dengan jangkauan yang lebih luas ke masyarakat dan potensi kecurangan yang minim, penghargaan oleh Kemenristek Dikti untuk para kolumnis media massa sangat kurang.
Di dunia pendidikan, dulu dikenal nama besar Mochtar Buchori yang produktif menulis artikel di banyak media massa nasional. Gagasannya dibaca banyak guru, mahasiswa, dan juga birokrat. Kumpulan artikelnya pun kemudian dikemas jadi buku yang dijadikan bacaan wajib mahasiswa di banyak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Ketersebaran yang luas menjadikan artikel populer potensial dikritik, dikoreksi, dan direspons secara luas juga, sehingga berkualitas dan tidaknya artikel akan jelas dapat dilihat.
Berbeda dengan buku atau artikel di prosiding yang terbit di lingkungan terbatas, hingga bisa saja penulis hanya mencetak 5 eksemplar buku ber-ISBN dan Hak Cipta serta dengan kualitas yang tidak terjaga, namun tetap dicatat sebagai "prestasi" yang dapat dihitung untuk mendapat tunjangan atau kenaikan pangkat.
Reputasi Intelektual
Oleh karena itu, kebijakan soal publikasi seharusnya ditekankan pada keterjagaan kualitas akademik dan tidak melulu menggantungkan diri pada Scopus. Kemenristek Dikti harus mencoba untuk merumuskan ulang pengertian publikasi bereputasi internasional, baik jurnal ilmiah, prosiding, maupun penerbit-penerbit buku internasional. Reputasi ilmiah sebetulnya dibangun oleh komunitas-komunitas intelektual yang pakar di bidangnya masing-masing. Scopus sebetulnya banyak yang mengkritik, dominasinya yang sangat hegemonik menjadikan banyak pihak mengkritik bias indeksasi Scopus-Elsevier, akses, dan soal orientasi bisnisnya (Jon Tennant, 2018, Hamonangan, 2019).
Oleh karena itu, kebijakan soal publikasi seharusnya ditekankan pada keterjagaan kualitas akademik dan tidak melulu menggantungkan diri pada Scopus. Kemenristek Dikti harus mencoba untuk merumuskan ulang pengertian publikasi bereputasi internasional, baik jurnal ilmiah, prosiding, maupun penerbit-penerbit buku internasional. Reputasi ilmiah sebetulnya dibangun oleh komunitas-komunitas intelektual yang pakar di bidangnya masing-masing. Scopus sebetulnya banyak yang mengkritik, dominasinya yang sangat hegemonik menjadikan banyak pihak mengkritik bias indeksasi Scopus-Elsevier, akses, dan soal orientasi bisnisnya (Jon Tennant, 2018, Hamonangan, 2019).
Beberapa pengelola dan komunitas ilmiah tetap saja tekun dan telaten merawat iklim akademik melalui penerbitan jurnal-jurnal bereputasi nasional maupun internasional tanpa peduli apakah diindeks oleh Scopus atau tidak. Para pakar dalam bidang-bidang tertentu juga tetap menulis dan mengirimkan manuskripnya ke jurnal-jurnal yang memang terjaga kualifikasinya, tidak peduli jurnal tersebut terindeks Scopus atau tidak. Semangat inilah yang benar dan harus dijaga serta dikembangkan di kampus-kampus kita. Oleh karena itu, Kemenristek Dikti harus merumuskan ulang bahwa jurnal bereputasi bukan hanya yang terindeks oleh Scopus dan sejenisnya.
Pemerintah juga hendaknya mendorong agar penerbit menjaga betul kualitas buku-buku akademik terbitannya. Caranya dengan menggandeng para pakar dari kampus sebagai bagian dari editorial board untuk menelaah, menyeleksi, dan memberi masukan calon naskah buku. Para akademisi juga harus memperluas perspektif, bahwa media massa sangat potensial sebagai sarana penyebaran gagasan dan temuan riset. Model-model kebijakan berlogika behavioristik reward-punishment seperti Scopus terbukti menghasilkan kartel sitasi dan jalan terabas asal terindeks Scopus. Untuk mengatasi hal tersebut, yang harus mulai digarap adalah mengembangkan komunitas epistemik di kampus-kampus, yaitu pengembangan pusat-pusat studi, publikasi jurnal ilmiah akademik, dan penerbitan buku yang berkualitas.
Penghargaan kepada peneliti yang masih minim-sekarang oleh Kemenristek Dikti, proposal penelitian tidak boleh mencantumkan honor peneliti (alasannya karena sudah masuk dalam remunerasi), dana penelitian yang masih minim, dukungan perkembangan pusat studi yang juga terbatas, barangkali menjadi faktor upaya mengembangkan iklim ilmiah di kampus relatif sulit. Terlebih ketika gaji dan tunjangan sebagai birokrat kampus yang jauh lebih banyak, maka aktivitas pengembangan keilmuan akan terlihat tidak menarik. Kebijakan soal Scopus bagai upaya potong kompas, yang ketika tidak diikuti penguatan komunitas-komunitas epistemik di kampus, tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kecurangan dan stagnasi perkembangan ilmu pengetahuan.
Perumusan ulang pengertian dan ukuran publikasi bereputasi internasional harus juga mencakup publikasi selain yang diindeks Scopus, dengan catatan jelas reputasinya. Berikutnya, penerbit perlu diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas seleksi naskah akademiknya, menulis di media massa perlu dilihat potensi besarnya dalam membangun wacana publik, pusat-pusat kajian perlu diberi ruang dan fasilitas yang cukup untuk berkembang, dan penghargaan terhadap aktivitas riset perlu lebih ditingkatkan. Resep-resep inilah kiranya yang akan lebih membangun iklim intelektual hingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas publikasi ilmiah dan populer para akademisi kita.
sumber: https://news.detik.com/kolom/d-4477199/scopus-dan-problem-kultur-akademik-kita

